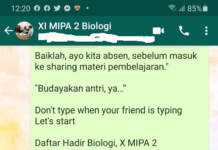Setetes air bening sudah memucuk di sudut mata, tidak terbendung, dan akhirnya, ia meluncur, membangun anak sungai di pipi. Mata saya pejamkan sembari menghirup napas perlahan. Sudut bibir saya tarik, sebuah senyum terpasang di wajah. Saya menikmati proses ketika gas oksigen memasuki rongga paru. Rasanya menyejukkan. Senyum masih terpasang di wajah. Benar-benar, hati saya saat ini seperti ditaburi bunga-bunga kebahagiaan. Saya tidak menyangka jika seindah ini takdir yang Allah lukiskan untuk saya, si hamba yang dhaif nun fakir.
Kebahagiaan. Sebuah kata yang sepertinya selalu dicari banyak orang. Banyak orang menggunakan beragam cara, demi menggapainya. Seperti bekerja keras, agar bisa memiliki harta berlimpah, sehingga mampu membeli barang-barang mahal dan mewah. Ada juga yang bekerja keras, untuk mendapatkan jabatan tinggi di sebuah perusahaan atau institusi. Pun tidak menutup kemungkinan, mencari istri atau suami yang berparas menawan, agar mendapatkan kehormatan sehingga kebahagiaan diraih. Semua arahnya kepada kebahagiaan.
Saya termenung, meski beberapa hal di atas merupakan standar yang biasanya dipakai oleh manusia dalam memaknai kebahagiaan, namun saya menemukan versi saya sendiri. Sebuah versi yang baru saya jumpai setelah saya menikah. Sebelumnya, yang menjadi acuan dari hidup dan kebahagiaan, kurang lebih sama dengan standar yang umum. Akan tetapi, setelah mendapatkan kuliah kehidupan dari dosen di universitas kehidupan yang saya ikuti, saya menemukan versi lain yang bahkan bertentangan dengan apa yang saya percayai sebelumnya.
Dosen yang disebutkan tadi adalah suami saya. Seorang partner hidup sekaligus guru kehidupan. Beliau memang bukan pegawai. Beliau bahkan tidak ingin terikat dengan perusahaan atau instansi lain. Prinsip beliau hanya satu hal, yakni beliau ingin menjadi seorang enterpreneur, meski memang harus memulai segalanya dari nol, meski memang harus memulai dari bisnis UMKM, asalkan beliau bisa menjadi bos di usahanya sendiri, bahkan syukur-syukur bisa membuka lowongan kerja dan menebarkan manfaat dari situ. Sebagai istri, tentu saya hanya bisa mendukungnya, mendoakannya, dan berjuang bersamanya. Meski memang usaha kami terdampak karena pandemi, kami tetap bersyukur. Sebab kami yakin seyakin-yakinnya, bahwa Allah memang sudah menjamin rezeki setiap hambaNya, setiap hari.
Mas selalu mengajarkan, bahwa untuk menggapai taraf kebahagiaan di puncak hakiki, sebisa mungkin kita menekan nafsu kita. Baik nafsu terhadap harta, benda, popularitas, dan segala hal yang bisa menyebabkan penyakit hati. Sulit sekali memang mempraktikkan apa yang beliau ujarkan. Terlebih, tidak munafik jika sering saya iri dengan pencapaian kawan-kawan seusia saya. Meski iri itu kadang saya tuangkan dalam bentuk motivasi dan pelecut, namun sering, motivasi itu malah menjerat saya sendiri. Sebab ranahnya, niatnya bukan untuk menggapai kehakikian, yakni rida dan cintaNya, melainkan sebatas pembuktian. Rasanya begitu kering dan hambar, jika hanya dunia yang dikejar. Dan yang pasti, mengejar dunia, rasanya sangat melelahkan.
Ketika sudah berada di puncak letih, mas suami menyampaikan kepada saya, bahwa sejatinya, apa yang saya cari jika saya sudah memiliki rumah, mobil, harta, baju-baju bagus, dan pekerjaan yang menjanjikan? Saya menjawabnya dengan kebahagiaan. Beliau hanya tersenyum. Beliau bahkan menyampaikan, bahwa sejatinya bahagia bisa digapai dari jalan sederhana. Kita tidak perlu menunggu untuk kaya agar bisa bahagia. Kita tidak perlu menunggu untuk punya kelebihan beras untuk membantu makan orang lain. Apa yang kita punya saat ini, jika kita mampu mensyukurinya dan membagikannya, kita bisa, dan sejatinya semua lebih dari cukup. Biar orang lain hidup dengan mewah, berganti-ganti baju bagus bermerek setiap hari, memiliki mobil mewah, juga rumah dengan perabotan yang mahal. Asalkan kita terus memupuk syukur, maka sejatinya, hidup kita sudah bahagia. Kita sudah menikah, banyak di luar sana yang seusia kami namun belum juga diperjumpakan dengan jodohnya. Kita sudah dititipkan buah hati, banyak pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun belum juga dititipkan buah hati oleh Yang Mahakuasa. Kita sudah memiliki rumah, tidak kontrak, meski memang sederhana. Kita juga memiliki mobil, meski mobil lama. Semuanya sudah cukup, lebih dari cukup. Keluarga diberikan kesehatan, bisa berkumpul dengan keluarga dalam keadaan baik-baik saja, maka kita tidak perlu peduli dengan apa kata orang di luar sana.
Saya hanya membeku ketika beliau menguliahi saya. Apa yang beliau sampaikan memang sesuatu yang hanya bisa saya dapatkan di universitas kehidupan. Pada akhirnya, konflik yang sempat memanas ketika saya masih keras dengan ego saya, perlahan mulai melunak, dan bahkan luntur. Kami saling menerima, saling bersyukur, saling mendoakan, dan saling memeluk terhadap apa yang hidup hadirkan. Jika kami mendapatkan rezeki, kami akan mensyukurinya, dan terus mengupayakan untuk dimasukkan dalam investasi usaha serta proyek-proyek kami ke depan. Tidak apa berjalan lambat, asalkan halal dan berkah, dan itulah sejatinya apa yang seharusnya kami cari.
Suami saya memang sederhana. Namun cinta yang beliau berikan kepada saya bukan sembarang cinta. Saya bahkan belum menemukan kata yang tepat untuk bisa mendefinisikan cinta yang beliau amalkan. Bahkan, setiap hari, tidak pernah sedetikpun terlewati dari kisah romansa dengan beliau. Selalu saja ada hal mengejutkan dan yang membahagiakan beliau siapkan untuk saya. Mengimbangi sifat saya yang lebih banyak seriusnya, beliau adalah seorang yang sangat humoris. Dan, saya tidak pernah bosan berada di sisi beliau. Yang ada malah rindu seperti dipupuk, semakin tumbuh subur di dalam hati.
Lakon kisah kami kali ini adalah tentang persiapan melahirkan si buah hati. Kami sudah membuat keputusan untuk menerapkan Long Distance Relationship sebelum acara selamatan tingkepan─tujuh bulanan─janin yang saya kandung. Saya akhirnya harus tinggal di Blitar─sampai bayi kami lahir, sedangkan beliau harus di Tulungagung untuk tetap menafkahi kami. Jika ditanya rindukah? Tentu sangat rindu. Terlebih, saya sudah terbiasa hidup dengan beliau, dengan cara-cara yang lemah lembut, dengan senyuman, dan jauh dari perlakuan serta kata-kata yang keras lagi kasar.
Akan tetapi, pagi kemarin, saya menelepon suami untuk menjemput dari Blitar untuk kembali ke Tulungagung. Saya akan kembali ke Blitar dalam lima hari, bareng dengan ibu Tulungagung yang akan buwuh di rumah bude. Mengapa saya meminta kembali di Tulungagung? Memang, tidak ada masalah apapun dengan ibu dan bapak di rumah. Hanya saja saya merasa, saya dan adik bungsu membutuhkan jarak sebentar. Pun saya juga sangat merindukan Mas suami. Itu saja.
Ketika mas suami tiba di Blitar, saya mengingat, bahwa hari itu adalah hari ulang tahun si bungsu. Saya sudah menyiapkan kado untuknya. Segera, kado saya ambil dari lemari pakain, dan saya serahkan kepada ibu. Saya meminta ibu memberikannya ketika makan malam tiba.
“Kenapa tidak menunggu besok, Nak?” tanya ibu. Jujur, sebenarnya saya lupa jika hari itu adalah hari H ulang tahunnya. Jika saya tahu, mungkin saya tidak akan berangkat. Namun nasi sudah terlanjur menjadi bubur, suami sudah tiba dan saya sudah siap untuk dijemput.
“Lain waktu saja, Ibu. Maaf.” Hanya itu yang terucap dari bibir saya.
Berita saya ingin ke Tulungagung memang sangat mendadak. Keputusan ini memang terkesan tiba-tiba. Tidak heran jika adik saya kedua dan ibu cukup terkejut. Saya memang hanya bercerita kepada bapak pagi tadi. Kemudian, kami kedatangan tamu bude dan Pak Puh, sehingga masing-masing sibuk dengan tamu.
Ketika kondisi rumah sudah tidak sehat untuk mental saya, saya memutuskan untuk angkat kaki saja. Keadaan saya yang hamil mendekati usia delapan bulan sebisa mungkin dihabiskan dalam atmosfer yang menggembirakan. Saya ingin bayi di dalam kandungan ini bahagia, tidak terus mendengarkan isak tangis dari ibunya. Entahlah, bagi saya, dalam keadaan hamil, saya merasa lebih sensitif. Mungkin karena perubahan hormon, dan rasa luar biasa yang dirasakan oleh tubuh, akhirnya hati semakin terasa sensitif. Jika dalam keadaan biasa saya mungkin bisa menanggung dan bersikap biasa saja, namun tampaknya berbeda ketika saya sedang hamil. Atau mungkin saya terbiasa dimanja dan disikapi dengan kelembutan dan kasih sayang oleh suami, sehingga sikap kasar dan sengit cukup mengiris-iris hati. Entahlah. Yang saya tahu, saya ingin ke rumah Tulungagung, menciptakan jarak sebentar, dan meluapkan rindu kepada suami.
“Nduk, Adikmu memang seperti itu. Kamu di sini kan tidak ada masalah dengan Bapak dan Ibu. Kamu di sini kan untuk Bapak dan Ibu,” ucap bapak, berusaha menghentikan.
“Saya memang tidak memiliki masalah dengan Bapak dan Ibu. Hanya saja, saya merasa butuh waktu untuk kembali. Mohon maaf, Bapak, Ibu.”
“Bapak saja setiap hari diperlakukan sengit, Nduk. Itu bapaknya. Kamu juga kakaknya, diperlakukan seperti itu. Kamu yang sabar ya Nduk,” pinta bapak.
“Ada masalah apa, Nduk?” Ibu bertanya.
“Ibu tentu paham, banyak sekali. Pertama teflon. Hanya karena saya menggunakan spatula besi bukan yang kayu, langsung disengiti. Padahal itu teflon lama, dan sudah mengelupas. Mengapa kok bisa lebih memilih benda dibandingkan dengan perasaan Mbaknya. Kemudian mie, dan type X,” jawab saya, sembari bercucuran air mata. Hati rasanya seperti dihantam ketika mengatakannya.
Ibu menjelaskan versi adik saya. Sepertinya si bungsu sudah bercerita kepada ibu. Saya hanya sambil lalu saja. Sebab, saya merasa terasing di tengah keluarga saya sendiri. Saya merasa tidak dianggap. Terlebih ketika mereka semua berkumpul. Akhirnya, saya lebih memilih untuk kembali di dekapan suami. Beliau bisa memperlakukan saya seolah saya seorang ratu. Daripada terus mengucurkan air mata dan tenggelam dalam samudra kepedihan, saya memilih untuk kembali kepada keluarga yang bisa menerima saya. Saya memang masih sangat merindukan bapak dan ibu. Namun karena keadaan seperti itu, saya harus bisa. Toh di sana nanti saya bersama suami, papa dari bayi yang saya kandung.
Di tengah ‘drama’ sebelum berangkat, mas suami sempat berusaha melucu. Beliau tentu iba ketika melihat istrinya berderaian air mata, meski saya memang tergolong cengeng, mudah sekali menangis, beliau tetap berusaha menghibur. Beliau mengambil tisu dan mengusap perut saya yang sudah besar.
“Cup-cup-cup,” ujar beliau, seolah-olah bayi kami yang menangis. Ibu tertawa, saya sedikit tersenyum, menghormati usahanya untuk kembali menerbitkan tawa di bibir. Ibu masih terus menjelaskan, dan ada sedikit kesan membela si bungsu. Saya hanya tersenyum tipis.
Akhirnya kami berangkat. Di jalan, ada rasa sesal yang menjalar. Mengapa harus di ulang tahunnya. Tapi ketika mengingat bagaimana perlakuannya, saya kembali menangis. Tidak heran, jika air mata masih saja merembes di sudut mata. Sesekali saya menyekanya. Bahu sedikit terguncang, terisak-isak. Meski sedang di jalan, mas suami tetap berusaha menghibur. Namun karena kami terpisah dengan helm, ditambah perut yang sudah besar, akhirnya saya tidak bisa mendengarkan ucapannya dengan jelas. Sesekali menimpali. Selanjutnya, saya hanya diam, terhanyut dengan pikiran saya sendiri.
Di jalan, rasa haus tiba-tiba datang di kerongkongan. Ah, dengan kecepatan 30 km/h, kemungkinan besar kami tiba sekitar tiga puluh menit lagi. Melihat saya masih belum mendapatkan momentum untuk tersenyum, suami masih terus berusaha melucu. Beliau menyebutkan ingin mengajak belok makan di warung bakso, tapi warungnya sedang tutup. Akhirnya, saya tergelak tawa. Kemudian ada juga warung es dawet serabi, beliau langsung mengatakan, “Kamu tidak boleh es, Dik.” “Lah kan nanti bisa beli tanpa es, Mas.” “Serabi tanpa es jadinya rabi. Enggak enak, Dik.” Beliau berkelakar. Saya langsung tertawa lepas. Ada saja ulah mas suami tercinta ini. “Tapi bukankah rabi itu enak, Pa?” timpal saya tidak mau kalah.
Tiba di perempatan Kunir, kami berbelok di salah satu Indomaret. Bagaimana bisa hati kami saling terpaut sedalam itu. Padahal saya tidak mengatakan secara eksplisit jika saya haus. Saya merasa tersanjung karena di perjalanan kami sebelum-sebelumnya, kami tidak pernah sekalipun berhenti sebelum tiba. Saya hanya mengucapkan alhamdulillah di dalam hati. Setelah selesai memarkir motor, beliau pun menyampaikan, “Mas beli kopi dingin ya.” “Mama mau.” “Enggak boleh kopi, enggak boleh es kamu, Dik.” “Ya sudah mama mau Pocari Sweat saja. Yang paling kecil, ya Pa.” “Oke, tunggu di sini.” Saya tersenyum. Saya diminta untuk duduk di kursi depan Indomaret tidak ikut masuk ke dalam. Mungkin biar tidak mengambil jajan, hehe. Maklum, Mas masih mencukupkan kebutuhan lainnya.
Setelah duduk di kursi, rasanya enak sekali. Rasanya lumayan pegal tulang-tulang di panggul setelah duduk di motor beberapa menit. Ketika helm saya lepas, wuuusss angin sejuk menyapa.
“Ini, Dik.” Mas keluar Indomaret sembari menyodorkan sebotol minum. Sikap manja saya keluar. Saya serahkan kembali botol itu kepada beliau.
“Bukain!” pinta saya. Sembari tersenyum, beliau membuka botol, dan segera memberikannya kepada saya. Setelah itu, kami meminum minuman kami masing-masing. Ketika air segar itu melewati kerongkongan, rasanya, ah mantab sekali. Dahaga seketika terusir dari sana. Setelah saya lihat, air tinggal separuh kurang. Memang, kalau soal minum, saya jagonya. Dari kecil memang diajarkan bapak dan ibu untuk suka minum air putih. Selepas itu, kami melanjutkan perjalanan.
Di jalan, kami menikmati semilir angin yang sejuk. Awan kelabu tampak berarak-arak di langit, menutup terik siang ini. Saya bersyukur sangat karena cuaca hari ini tidak panas. Jika panas, mungkin saya akan sangat rewel karena perjalanan jauh.
Saya memang memilih untuk melepas helm, agar dagu saya bisa menempel di pundak mas suami. Pun karena saya sudah tidak kehausan, akhirnya kami bisa menghabiskan waktu perjalanan dengan canda dan tawa. Sering sekali saya merasa gemas dengan Mas suami. Tubuhnya gendut, tapi menggemaskan, juga ditambah sifat humoris beliau yang selalu membuat saya tergelak-gelak. Selain itu, di jalan, beliau juga sering sekali mencubit-cubit kaki saya. Kata beliau, kaki saya menjadi besar sekali. Akhirnya beliau sangat gemas. Mulanya saya memang suka manyun ketika dikatakan membesar. Namun setelah saya melihat cermin dan neraca badan, baiklah saya mengamini ucapan beliau. Mau mengelak bagaimana lagi jika memang begitulah fakta saat ini. Dan kembali kami melakukan presensi warung-warung di pinggir jalan.
Ada warung bakso di seberang jalan, ramai pengunjung, dan menjual bakso jumbo. Sepertinya menggiurkan. Tapi saya sedang tidak berminat makan bakso. Hanya untuk menggoda suami, saya pun menyeletuk, “Mas itu loh, warung bakso jumbo.”
“Istriku sudah jumbo. Saya tidak berminat lagi dengan yang jumbo-jumbo lainnya.”
“Hahahahaaa…”
“Lagi pula, itu di seberang jalan. Ribet nanti menyeberangnya,” ucap beliau. Saya semakin gemas.
“Awas saja habis melahirkan Mama akan diet lagi. Diet ketat biar cuantik kembali. Mamah muda harus cantik cetar nanti,” bela saya.
Kami pun menghabiskan waktu dengan terus mengobrol. Sudut mata saya yang tadinya sembab, sudah mengering. Saya bahkan lupa dengan kesedihan yang sempat mengiring kepulangan tadi.
Tiba di Ringinpitu, tiba-tiba ada jenang campur. Langsung saya meminta Mas suami untuk membelikan. Ingin sekali makan jenang campur. Sudah lama lidah tidak merasakannya.
Mas langsung mengajak kembali ke warung jenang campur, dan kali ini benar-benar dituruti. Bahkan ketika menunggu penjual menyiapkan pesanan, Mas membelikan saya cilok untuk camilan. Saya tersenyum, tidak berhenti tersenyum.
“Terima kasih, Cinta.” Saya mengucapkannya sembari menatap matanya. Tubuhnya yang gembul benar-benar membuat saya gemas. Kami akhirnya menikmati santapan cilok, satu cup berdua, namun diberi dua tusuk oleh si penjual. Tiba-tiba mas suami menaruh tusuknya dan terdiam. Saya paham, beliau minta disuapi. Dengan peka dan penuh dengan kesadaran, beliau pun saya suapi, lahap sekali. Sesekali, saya terus menatap beliau. Karena Mas suami baru mencukur kumisnya, beliau tampak lebih muda dibanding ketika kumisnya masih tebal. Sejatinya beliau memang masih muda. Kami sebaya. Beliau hanya sudah menginjak usai 26 tahun, sedangkan saya 25 tahun. Meski demikian, usia kedewasaannya jauh melampaui usia tubuhnya. Mungkin pemikirannya setara dengan orang berusia 40 tahunan. Beliau sangat dewasa dan sangat paham bagaimana cara memuliakan dan memperlakukan saya, istrinya. Adalah sebuah anugerah terindah dari Allah Swt., yang telah menakdirkan saya menjadi istrinya.
Setelah pesanan kami rampung, kami melanjutkan perjalanan pulang. Begitu tiba, saya langsung ke dapur, salim dan memberikan jenang campur kepada ibu. Sedangkan sisanya kami bawa ke kamar. Saya langsung membuka satu cup jenang. Milik suami saya tawarkan untuk dimakan sekalian atau tidak, beliau menjawab nanti saja. Akhirnya setelah milik saya habis, beliau malah meminta saya menghabiskannya. Memang jenangnya enak. Santannya asli, kental dan masih segar. Sedangkan rasa jenangnya juga tidak abal-abal.
“Terima kasih, Papa.”
“Terima kasih buat?”
“Buat semuuaanya,” ucap saya sembari tersenyum.
Beliau pun mencium kening saya. Saya kembali lagi di ruang kamar yang banyak sekali memori indah terajut dengan suami. Segera, barang-barang saya keluarkan dan saya tata. Sedangkan suami saya, sudah ditunggu pelanggannya. Selanjutnya, saya merebahkan badan.
“Alhamdulillah, sudah tiba dengan selamat, ya anakku sayang. Sekarang sudah dekat dengan papa. Rindu kita terobati.”
Saya merebahkan badan sembari menutup mata. Semilir sejuk yang datang dari kipas angin mengempas peluh. Bagaimanapun, meski mungkin jarak tercipta dengan keluarga saya sendiri, mereka tetap keluarga. Saya harus bisa belajar memaafkan, meski mungkin kata maaf tidak saya dengar. Air mata kembali merintik. Saya tidak ingin melupakan luka yang masih basah. Namun saya ingin menikmati rasa sakitnya, juga proses penyembuhannya. Saya tidak ingin menunggu datangnya pagi, ketika malam tiba. Pun saya tidak ingin menunggu senja, ketika pagi tiba. Saya ingin menikmati dan mensyukuri setiap detik proses dan lakon dalam hidup ini.
Tulungagung, 12 Februari 2021