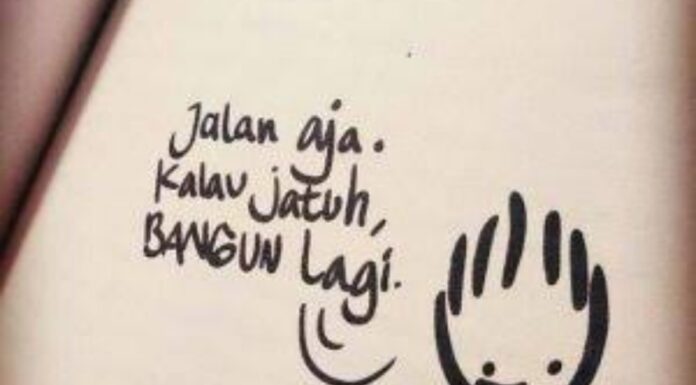Oleh: Muhammad Abdul Aziz
Ketika masih belajar di Gontor dulu, satu hobi yang paling saya suka adalah bertengger di tepi etalase depan markas Itqan Agency. Di situlah perkenalan saya dengan Republika bermula. Saya akan selalu menyambangi hampir saban hari rubrik Opini. Biasanya selepas makan siang. Dengan sarung masih terikat tali pinggang. Lalu tangan kiri mencengkeram piring biru itu.
Masih lekat dalam ingatan seorang penulisnya bernama Fadli Zon. Beralmamater di London School of Economics. Agresifitas darah mudahnya tampak sangat dalam tulisan tersebut. Dan seiring perjalanan waktu, akhirnya ia pun menghiasai layar kaca perpolitikan Indonesia.
Resonansi tentu tidak akan luput. Saya amat menyukai gaya tulisan Zaim Uchrowi. Ia selalu akan memulai artikelnya dengan sebuah cerita kehidupan yang sangat realis. Sama sekali tidak jauh dari kenyataan harian kita. Apa adanya. Yang menarik selanjutnya adalah kemampuannya untuk mensintesakan realitas tersebut dengan humanisme, spiritualisme, kebudayaan, kepekaan sosial, dan sastra.
Meski tidak sesering Resonansi dan Opini, saya juga sering mengunjungi rubrik Hikmah. Dan tepat pada titik hari ketika itu, yang hingga sekarang saya ingat, disebutkan bahwa kata umm, yang bermakna ibu, berasal dari amma ya’ummu. Artinya, menuju. Oleh itu, tidak terlalu jauh jika sekiranya kita mengartikan umm sebagai tempat yang dituju. Tempat kembali.
Rasanya kita tidak memerlukan penjelasan lebih detail lagi tentang fakta bahwa ibu adalah memang tempat kembali para anaknya. Bagi saya sendiri, setelah mendapatkan anak yang pertama ini, Akhsya, saya baru merasakan benar bagaimana hubungan cinta yang terbangun antara seorang ibu dengan anaknya. Ketika balik kampung kemarin, entah bagaimana ceritanya, Akhsya mau begitu saja saya gendong. Padahal sudah hampir tiga bulan saya meninggalkannya.
“Keroso bekne,” kata Budhe Zun-nya yang selalu ikut ngemong.
Tapi kedekatan tersebut tidak sedekat ia dengan ummi-nya. Jika bertemu dengan seorang asing, apalagi dari jenis perempuan, maka si Akhsya cenderung takut dan tidak akan mau digendong. Ia akan meneriakkan jeritan buta, sampai air matanya menganak sungai di pipinya.
“Iki ora tangisan gajah iki,”seloroh ummi-nya.
Melihat air matanya yang melimpah di pelupuk matanya, rasa haru saya berkecamuk. Antara iba dan bahagia. Iba lantaran melihat tangisannya. Dan ternyata tangisan itulah yang juga menyelenggarakan kebahagiaan. Keduanya bercampur baur menjadi satu.
“Inikah yang disebut cinta?”
“Beginikah rasanya menjadi seorang ayah?”
“Ayah delapan bulan.”
Dalam situasi seperti ini, maka obat yang paling mujarab adalah kembali ke pelukan Ummi-nya. Fenomena ini rasanya bukan hal baru dalam relasi antara seorang ibu dan anak. Siapa saja daripada seorang anak, kecil ataukah besar, akan merasa tenang ketika ia kembali kepada ibunya. Tentu tidak hanya anak. Bahkan sang suami pula, tempat kembali mereka adalah dalam ketenteraman yang disiramkan oleh cinta kasih istrinya. Litaskunū ilayhā.
Hamka menuturkan bahwa salah satu cira orang berkepribadian besar adalah bersemayamnya cinta dalam dirinya. Cinta kepada dirinya sendiri. Cinta kepada keluarganya. Kepada sesamanya. Kepada masyarakatnya. Kepada kemanusiaan. Dan lebih penting lagi cinta kepada umatnya.
Jika kita telisik lebih dalam, kita boleh jadi akan dengan tidak sadar menemukan fakta bahwa kata ummat pun ternyata seakar dengan umm.
Lalu apa relevansinya antara seorang ibu dan ummat?
Ummah mempunyai banyak makna dalam al-Qur’an. Sangat beragam dari satu ke lainnya. Al-Raghib al-Ishfahani menyebutkan dalam kitabnya Mufradāt Alfādz al-Qur’an, bahwa umat adalah segolongan manusia yang berkumpul atas dasar agama tertentu, atau tenggat waktu tertentu, pada suatu tempat, baik atas inisiatif mereka sendiri atau bahkan karena keterpaksaan.
Jika definisi ini dikaitkan dengan umat Islam, maka yang menjadi tali pengikat berkumpulnya umat Islam adalah “innamā al-mu’minūn ikhwah.” Yaitu, iman di dada mereka. Hal ini merupakan kelebihan umat Islam di tengah dunia hari ini yang dipenuhi pada fanatisme geografis, sosiologis, kultural, dan antropologis.
Urgensi ummat dalam paradigma seorang Muslim juga dapat dilihat melalui keberadaan ta’ marbuthah di akhir hurufnya. Sebagaimana yang kita tahu, salah satu faidah tambahan ta’ marbuthah adalah untuk menunjukkan urgensi yang amat dalam. Sebagaimana hadith Thalab al-‘ilmi, kata setelahnya bukan faridh yang memang mudzakkar. Tetapi malah faridhah yang justru mu’annats. Arti yang timbul kemudian adalah menuntut ilmu bukan hanya wajib, tapi sangat wajib.
Dari sini kita dapat mengartikan bahwa ummat itu bukan sekadar tempat kembali. Tapi ia adalah tempat kembali yang utama. Tempat di mana kita mengembalikan segala pengabdian kita – tentu saja masih di bawah keridlaan Allah Swt. Kembali kepada ummat berarti ia memiliki paradigma keummatan dalam berfikir untuk kemudian diterjemahkan dalam lakunya. Dengan kata lain, ia sama sekali tidak mementingkan dirinya sendiri, atau kelompoknya sendiri. Yang ada dalam fikirannya adalah hanya untuk kebaikan umatnya.
Aspek altruisme seperti inilah yang sulit untuk ditemukan di doktrin-doktrin agama lain dunia. Oleh itu, tidak salah rasanya jika apa yang selalu difikirkan Rasulullah Saw sejak zaman mudanya sehingga ajal menjemput kecuali “ummati, ummati.” Sebuah wejangan kepada umatnya untuk tetap berpegang pada tali Allah Swt. Sekaligus teladan luhur bahwa yang menjadi fokus tumpuan dalam hidup ini adalah sejauh mana kita mampu berkontribusi untuk ummat kita. Khayr al-nās anfa‘uhum li al-nās.
Dan jika yang kita bicarakan adalah keteladanan, maka amma ya’ummu di atas masih juga berkelindan dengan satu perkataan lain: imām.
Lalu apa relevansinya antara ibu dan imam?
Imām ber-wazn “fi’āl” yang salah satu faidahnya adalah bermakna ism al-maf’ūl. Menjadi obyek. Ilāh disebut Tuhan karena ia berasal dari kata alaha ya’lahu yang artinya menyembah. Dan Tuhan adalah Dzat yang disembah. Pun juga dengan kitāb, yang berakar dari kataba yaktubu; menulis. Dan tidak diragukan lagi, kitab adalah sesuatu yang ditulis. Maka hal senada juga berlaku dengan perkataan imām. Seorang pemimpin. Imam, oleh karenanya, bermakna sosok yang di mana seluruh perhatian ma’mum tertuju kepadanya. Ia lah sosok yang mesti diikuti. Dalam lakunya. Dalam khusu’nya.
Sebagaimana umm; seorang ibu. Ia adalah “madrasatun ūlā”. Sekolah pertama bagi setiap anak. Ibulah yang paling pertama dilihat oleh anaknya. Ia lah yang paling dekat dengan mereka. Ia lah yang paling berpotensi menjadi teladan luhur bagi anak turunnya. Sumber inspirasi. Ia juga tempat kembali dalam sebak dan ria. Bagi anak, juga suaminya. Ia lah wanita terbaik di mata setiap anaknya. Betapa pun pasti ia menyisakan kekurangan.
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق
Al-umm madrasatun idzā a’dadtahā A’dadta sya’ban ṭayb al-a’rāq
Selamat Hari Ibu.
Wallahu A’lam.